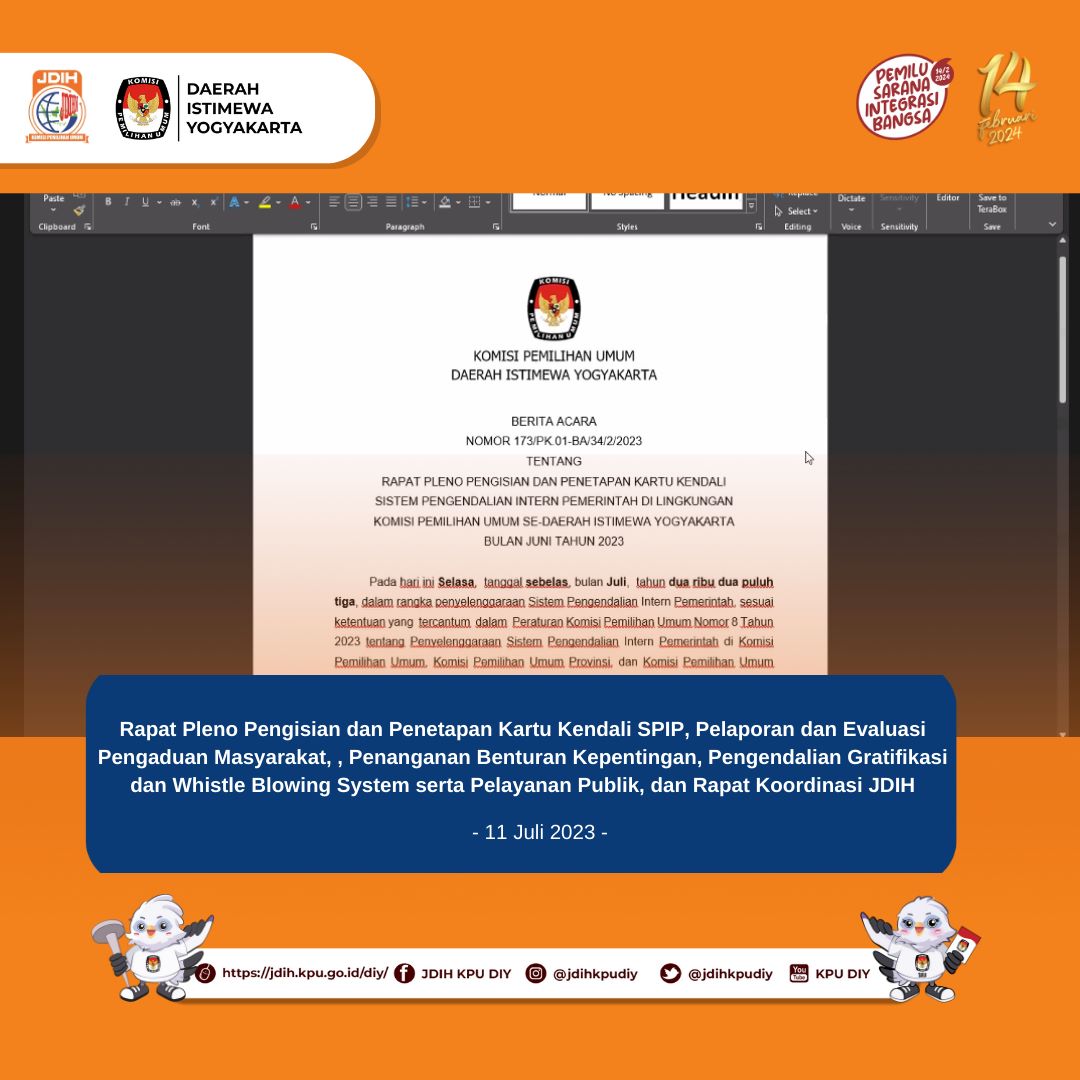Kajian Hukum Kritis Mewacanakan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik

Kajian Hukum Kritis Mewacanakan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik
(Ahmad Anfasul Marom)*
Parpol (Partai Politik) merupakan bagian penting dalam sistem kepemiluan dan sistem pemerintahan. Hampir semua jabatan publik di negeri ini ditentukan atau tidak lepas dari unsur partai politik baik itu secara langsung maupun tidak misalnya Pemilihan Presiden, DPR, Gubernur BI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Walikota, Bupati, dll. Sayangnya, dalam 10 tahun terakhir ini banyak operator ‘mesin produksi’ tersebut yang terserang penyakit akut sehingga harus berhenti dan berakhir di bui.
Sebut saja, Anas Urbaningrum (Ketua Partai Demokrat), Lutfi Hasan Ishak (PKS), Zulkarnain Djabar (Partai Golkar). Prilaku korup yang dilakukan oleh para pengurus teras parpol tersebut bisa saja karena kepentingan pribadi atau jamaah partai, akan tetapi yang jelas mereka telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memburu rente ekonomi dan bisa dijerat melalui sistem hukum pidana. Sedangkan secara kelembagaan pertanggungjawaban hukum pidana bagi partai politik belum menemukan arahan konsep yang jelas.
Tulisan ini, berusaha mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana partai politik melalui pendekatan konstitusi. Ada dua pertanyaan yang coba penulis ajukan di sini. Pertama, Bisakah parpol dimintai pertanggungjawaban pidana secara kelembagaan apabila ada salah satu pengurus atau anggotanya yang terjerat korupsi? Kedua, Bentuk pidana semacam apakah yang dapat dijatuhkan kepada partai politik tersebut?
Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Meminjam pendapat Schaffmeister ada tiga unsur dalam perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang, larangan yang ada dalam UU, dan ancaman bagi siapa saja yang melanggar (Terj. J.E. Sahetapy, 1995). Di Indonesia perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana dipisah secara tegas. Perbuatan pidana hanya mencakup dilarangnya suatu perbuatan, sementara pertanggung jawaban pidana mencakup dapat tidaknya pelaku dikenai pidana. Dasar perbuatan pidana adalah asas legalitas dan dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Dalam konteks ini Pompe (W.P.J., Pompe,1959) berpendapat bahwa: “... dat geen straf wordt toegepast, tenzij er een wederrehtelijke schuld te wijten gedraging is. Daar in ons recht geen schuld bestaat zonder wederrechtelijkheid kan men de kern der theorie dus kor formuleren als: geen straf zonder schuld”. (...Tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan).
Jadi, untuk mempidana orang tidak cukup hanya dengan alasan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi masih diperlukan syarat adanya kesalahan (schuld) yang menjadi dasar pencelaan terhadap pelaku (Mezger 1937). Kesalahan yang dimaksud setidaknya mengandung empat hal yaitu:
1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Hubungan batin pelaku terhadap perbuatan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pelaku.
4. Adanya unsur pencelaan.
Meskipun teori schuld di atas masih terbatas pada kesalahan yang diukur dari perbuatan pidana dengan subjek orang (naturlijk persoon), akan tetapi bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subyek hukum lainnya seperti korporasi misalnya.
Dan yang dimaksud korporasi di sini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum (BPHN, 2010). Dalam beberapa kasus, korporasi seringkali dijadikan sarana oleh para pengurus untuk memperoleh keuntungan meskipun mereka tahu risiko dari perbuatan pidananya. Oleh karena itu, perlu kami tegaskan bahwa korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Berangkat dari pemikiran tersebut penulis memberanikan diri untuk mengkaji bagaiamana kalau organisasi parpol dikategorikan sebagai badan hukum.
Parpol Sebagai Subyek Hukum Pidana
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa: “ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sedangkan mengenai partai politik sebagai badan hukum ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011, bahwa: “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum”. Pasal ini menegaskan asumsi penulis bahwa partai politik bisa jadikan subyek hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban hukum. Yang masih menjadi ‘PR’ kita saat ini adalah apakah partai politik itu tergolong badan hukum perdata (private) atau badan hukum publik karena ia memiliki karakteristik tersendiri.
Apabila kita lihat dari sisi pendirinya parpol bisa saja dimasukkan dalam kategori badan hukum perdata karena yang mendirikan bukan negara. Namun kalau kita melihatnya dari sisi kepentingan lembaga, partai politik tidak bisa dikategorikan sebagai badan hukum perdata karena tidak hanya mewadahi kepentingan pengurus atau anggotanya melainkan juga masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata terletak pada apakah ia mempunyai peran dalam mengambil keputusan atau membuat produk hukum yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut (Sutan R.S., 2006).
Meskipun partai politik tidak memiliki kekuasaan secara langsung dalam mengambil keputusan dan membuat peraturan perundang-undangan, namun secara umum partai politik khususnya yang memenangkan pemilu pengaruhnya sangat besar dalam membuat peraturan dan menentukan arah kebijakan publik. Oleh sebab itu, tidak heran kalau kemudian partai politik juga disebut sebagai badan hukum publik. Di sisi lain ia juga bisa dilihat sebagai badan hukum privat yang menyandang hak dan kewajiban layaknya subyek hukum perdata. Dari persilangan ini penulis menyebutnya sementara sebagai badan hukum ganda.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik
Sebagaimana yang telah penulis bahas di atas, secara teoritis subyek hukum pidana selain orang juga dapat berwujud korporasi. Jika kita mengidentifikasi bahwa suatu korporasi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, maka partai politik dapat masuk dalam kategori korporasi dan menjadi subyek hukum dalam ranah hukum pidana. Selain itu, merujuk pada UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Lingkungan Hidup, dan Rancangan KUHP, secara tegas menyatakan bahwa subyek hukum tidak hanya orang (naturlijk persoon) tetapi juga korporasi (recht persoon).
Berdasarkan argumentasi tersebut maka partai politik dapat digolongkan menjadi korporasi. Namun demikian, bukan berarti ini mampu menjamin bahwa pelaksanaan pemidanaan dan/atau pertanggungjawaban korporasi dapat dijalankan dengan mulus mengingat belum ada satu pun partai politik yang secara kelembagaan dijatuhi sanksi pertanggungjawaban pidana meskipun pengurusnya telah menjalani hukuman penjara. Sub bab ini berusaha menjawab dari dua pertanyaan yang telah penulis rumuskan dalam awal pembahasan.
Sejak tahun 1944 beberapa negara telah sepakat bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya mens rea dengan menggunakan asas identifikasi (Barda, 1998). Menurut asas tersebut perbuatan pengurus suatu korporasi dipersamakan dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Pemahaman ini didasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum karena tindakannya melekat pada hak atau kewenangan korporasi yang bersangkutan bukan atas kewenangannya pribadi.
Dalam teori fungsional sebuah lembaga bisa saja dikenakan sanksi pidana meskipun ia secara langsung/fisik tidak melakukannya sendiri alias dilakukan oleh pegawainya (Mardjono, 1993). Saya rasa konsep ini dapat digunakan dalam konteks pertanggungjawaban partai politik sebab tindakan partai sebagai korporasi selalu diwujudkan dalam perbuatan manusia sehingga pertanggungjawaban perbuatan perorangan tersebut menjadi perbuatan lembaga. Hal ini dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dan tunduk pada anggaran dasar partai politik.
Selanjutnya, menambahkan pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro yang dimaksud kesalahan (schuld) dalam pertanggungjabawab partai politik bukanlah kesalahan bathin sebagaimana yang dipahami dalam arti psikologis. Kesalahan itu harus dilihat dari segi dapat dicela atau tidaknya suatu perbuatan misalnya parpol sebenarnya bisa menyatakan sikap penolakannya atas revisi UU KPK akan tetapi karena situasi tertentu dan pertimbangan ‘aman’ ia tidak melakukannya justru mendukungnya. Prilaku parpol semacam itu berpotensi untuk dicela atau disalahkan masyarakat. Dalam hal ini partai memang sengaja atau lalai sehingga memungkinkan terciptanya situasi perbuatan pidana.
Sanksi Pidana Partai Politik
Untuk mengkaji sanksi pidana partai politik sebagai badan publik perlu penulis paparkan terlebih dahulu beberapa kasus pidana yang telah menjerat pengurus partai politik sepanjang 7 tahun terakhir ini. Kasus-kasus tersebut ditangani menggunakan UU Korupsi dan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setidaknya ada dua kasus tindak pidana korupsi dan TPPU yang melibatkan para petinggi partai politik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam keterangan yang disampaikan di meja persidangan, terdakwa mengungkap fakta bahwa ada aliran dana hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang mereka lakukan tersebut masuk ke dalam tubuh partai.
Akan tetapi pengakuan kedua terpidana korupsi tersebut secara institusional tidak berdampak pada partai yang bersangkutan karena pihak penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menjerat pada subyek orangnya. Padahal jika bertolak pada pemahaman UU nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang subyek hukum pidana tidak hanya terbatas pada orang saja melainkan juga korporasi atau dalam hal ini adalah partai politik.
Ketentuan yang harus diikuti untuk mencari ada tidaknya keterlibatan korporasi/partai politik diiatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi.
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Apabila partai politik terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka korporasi (parpol) tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6. Hal itu tercantum sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Sedangkan bentuk sanksinya tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)”.
Selain itu UU Nomor 8 tahun 2010 juga mengatur tentang sanksi pidana tambahan berupa:
1. Pengumuman putusan hakim.
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
3. Pencabutan izin usaha.
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
5. Perampasan aset korporasi untuk negara.
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.
Dari ketentuan pasal 6 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa suatu korporasi yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang baik itu pelaku aktif (Pasal 3 dan 4) maupun pasif (Pasal 5) dapat dikenakan sanksi pembubaran sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 6 (2) huruf d. Namun demikian, penjatuhan putusan pembubaran tersebut tetap bergantung pada kearifan hakim sebab pidana tambahan berupa penjatuhan pidana pembubaran dan/atau pelarangan korporasi merupakan pidana tambahan yang bisa dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
Terakhir ingin penulis tegaskan bahwa artikel ini hanyalah bentuk ijtihad penulis dalam mengangkat isu pertanggungjawaban pidana partai politik yang selama ini jarang tersentuh oleh para ilmuwan, peneliti, dan penggiat hukum.
Daftar Pustaka
Arif, Barda Nawawi,1998, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Laporan Akhir.
D. Simon, 1937, leer boek Van Het Nederlandsche Strafrecht, tweede deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia.
D.Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H Sutorius, 1995, Hukum Pidana, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
Reksodiputro, Mardjono, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawabanya”, (Pidato Dies Natalis Perngguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke 47, Jakarta 17 Juni 1993).
Sjahdeni, Sutan Remy, 2006, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
W.P.J Pompe, 1959, Hanboek Van Het Nederlandse Strafrecht, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschapij W.E.Jtjeenk Wilink, Zwolle.
*Penulis adalah Komisioner KPU DIY